Pengantar Menyelami Buku Manusia-manusia Paling Misterius di Dunia
Eka Nada Shofa Alkhajar
Menguak Mitos dan Legenda dalam Balutan Industri Budaya [1]
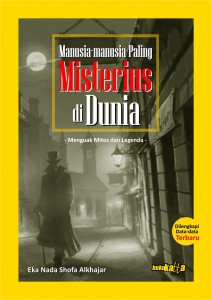 Dewasa ini industri budaya (culture industry) kian menyeruak sebagai fenomena. Berbagai sisi kehidupan manusia sepertinya tidak dapat lepas dari infiltrasi fenomena tersebut. Termasuk di dalamnya adalah mengenai mitos atau legenda dari sebuah enigma pun tak luput darinya. Secara jujur kalau kita ingin menilik lebih ke dalam nampaknya industri budaya telah merasuk jauh ke segenap relung serta sendi dunia realitas kita baik dalam makna sesungguhnya atau sekedar metafisika. Nicholas Garnham dalam tulisannya “On the Cultural Industries” (1997) [2], menjelaskan bahwa industri budaya merujuk pada institusi-institusi dalam masyarakat yang mengolah moda khusus produks dan organisasi korporasi guna memproduksi dan menyebarkan simbol-simbol dalam bentuk benda-benda dan jasa budaya sebagai suatu komoditas.
Dewasa ini industri budaya (culture industry) kian menyeruak sebagai fenomena. Berbagai sisi kehidupan manusia sepertinya tidak dapat lepas dari infiltrasi fenomena tersebut. Termasuk di dalamnya adalah mengenai mitos atau legenda dari sebuah enigma pun tak luput darinya. Secara jujur kalau kita ingin menilik lebih ke dalam nampaknya industri budaya telah merasuk jauh ke segenap relung serta sendi dunia realitas kita baik dalam makna sesungguhnya atau sekedar metafisika. Nicholas Garnham dalam tulisannya “On the Cultural Industries” (1997) [2], menjelaskan bahwa industri budaya merujuk pada institusi-institusi dalam masyarakat yang mengolah moda khusus produks dan organisasi korporasi guna memproduksi dan menyebarkan simbol-simbol dalam bentuk benda-benda dan jasa budaya sebagai suatu komoditas.
Senada dengan Garnham, Fiske mengurai bahwa industri budaya memproduksi “repetoir” barang-barang ataupun jasa dengan harapan menarik khalayak dan menyertakan khalayak sebagai konsumen komoditas tersebut (dalam Storey, 2007: 32) [3]. Dengan kata lain, ada suatu komodifikasi terhadap berbagai mitos atau legenda dari manusia-manusia yang dapat dikatakan misterius tersebut. Bentuk komodifikasi itu dapat berupa film, game, novel, buku, serial televisi sampai pada berbagai pertunjukkan hiburan bahkan pariwisata. Merujuk Gerald Sussman (1997), hal ini merupakan sebuah industri baru yang melakukan komodifikasi terhadap segala sesuatu. [4]
Dalam Webster’s New World Encyclopedia (1992), komodifikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “comodification” dimana akar kata tersebut adalah “comodity” yakni “something produced for sale”. Komoditas merupakan suatu objek. [5] Sementara, komodifikasi itu sendiri adalah proses—meminjam uraian dari Mosco (2009) adalah suatu cara dimana kapitalisme berupaya mengakumulasi modal (capital) [6]. Singkat kata, adalah suatu transformasi atau perubahan dari nilai fungsi atau guna menjadi nilai tukar.
Kapitalisme sendiri menurut Karl Marx merupakan suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumberdaya produksi vital yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan maksimal. [7] Akan tetapi tidak hanya itu, kapitalisme sebagai mode of production kini telah masuk ke berbagai ranah kehidupan baik politik, sosial, budaya dan sebagainya.
Bahkan Francis Fukuyama dalam tesisnya mengatakan bahwa setelah kapitalisme dan demokrasi liberal muncul serta berkembang maka hal ini merupakan tahap akhir dari proses penciptaan ide dalam sejarah. Dengan kata lain, ke depan tidak ada ide baru. Tidak ada lagi peristiwa-peristiwa dan kemajuan-kemajuan besar lain di dunia ini yang dipandang penting untuk dicatat dalam majalah, surat kabar, radio, televisi dan media massa atau elektronik lainnya. Kapitalisme maupun demokrasi liberal Amerika Serikat sebagaimana diurai Fukuyama akan menjadi panutan di dunia dan dengan demikian berakhirlah sejarah dunia. Akan tetapi tesis ini sebenarnya sudah patut dimuseumkan apalagi dalam memahami peradaban kontemporer karena sejarah sejatinya merupakan siklus yang terus berputar. [8] Tentu kita bersama mengetahui bahwa Amerika Serikat kini sedang mengalami permasalahan dalam ekonominya dimana China kini merupakan kreditor terbesar bagi negara adidaya tersebut.
Kritik terhadap Industri Budaya
Salah satu tulisan Adorno dan Horkheimer berjudul “The Culture Industry–Enlightenment as Mass Deception” dalam Dialectic of Enlightenment (1972) mengungkapkan kritiknya mengenai industri budaya. Sebagai penganut aliran kritis mazhab Frankfurt, mereka menilai bahwa kini kebudayaan didominasi berbagai komoditas yang diproduksi oleh industri budaya dimana komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh industri budaya diarahkan oleh kebutuhan untuk menyadari nilainya di pasaran dimana motif keuntungan menentukan berbagai bentuk budaya yang akan dijual. [9]
Adorno dan Horkheimer menilai bahwa kapitalisme dalam era modern menyediakan dan mengadakan industrialisasi terhadap semua hal termasuk waktu luang dan area budaya kehidupan yang tidak pernah diperhatikan produk kapitalis sebelumnya dimana kapitalisme didorong oleh logika mencari dan kemudian memenuhi pasar-pasar baru. [10] Dari sini akan dihasilkan suatu budaya massa atau budaya populer yang merupakan produk nyata dari pencerahan semu kapitalisme. Pencerahan semu adalah pencerahan melalui komoditas dan komodifikasi seluruh aspek kehidupan. [11]
Budaya Populer (Pop Culture)
Komoditas-komoditas yang diproduksi dan dilemparkan kepada khalayak perlahan tapi pasti akan menjadi budaya massa atau budaya populer yang sangat menjanjikan peluang pelipat gandaan kapital dari budaya populer itu sendiri. Apalagi budaya populer itu sudah merasuk dan hidup ditengah-tengah khalayak dimana yang diperlukan kapitalisme hanyalah memproduksi ulang dengan berbagai variasi yang berbeda untuk kemudian dijual kembali kepada khalayak. Dalam arti diproduksi dan direproduksi untuk mencari nilai lebih dari nilai tukar (exchange-value). [12]
Salah satu alat ampuh dalam upaya penyebaran budaya populer ini adalah media massa. Merujuk pada pandangan Stuart Hall, media massa merupakan instrumen yang penting dari kapitalisme abad ke-20 bahkan hingga saat ini. [13] Ini tidak lepas bahwa media massa dengan berbagai bentuknya, meminjam istilah Jean Baudrillard dalam In the Shadow of the Silent Majorities (1983)—media mempunyai logika sendiri dalam menangkap “realitas”. Realitas disini tentunya adalah berbagai mitos ataupun legenda ada maupun berkembang dalam masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena realitas tersebut telah masuk ke dalam sebuah industri budaya (culture industry). [14]
Dominic Strinati mengingatkan bahwa budaya populer harus dipandang sebagai sekumpulan genre, teks, citraan dan representasi yang bermacam-macam dan bervariasi yang dapat dijumpai dalam berbagai media. [15] Secara lebih mudah mitos dan legenda yang ada dapat dikatakan merupakan suatu teks sehingga kalaupun harus membaca setidaknya kita tengah membaca suatu teks populer. Dan tidak dapat ditutupi, para penggemar adalah bagian paling tampak dari khalayak teks dan praktik budaya populer. [16]
Henry Jenkins mengatakan salah satu ciri utama yang menandai moda pemberian (makna) budaya penggemar dalam teks-teks media adalah dengan melihat cara penggemar menarik teks mendekati ranah pengalaman hidup mereka, peran yang dimainkan melalui pembacaan kembali dalam budaya penggemar dan proses yang dengannya informasi program dimasukkan ke dalam interaksi sosial yang terus menerus. [17]
Sebagaimana diuraikan Jenkins: Teks ditarik mendekat bukan agar penggemar bisa dimiliki olehnya melainkan sebaliknya agar penggemar bisa lebih penuh memilikinya. Hanya dengan mengintegrasikan isi media kembali dalam kehidupan sehari-hari media, hanya dengan keterlibatan yang karib dengan makna dan materinya, para penggemar bisa mengonsumsi fiksi dan menjadikannya sebagai sumber daya yang aktif. [18]
Dalam Bond and Beyond (1987), Tony Bennett dan Janet Woollacott mengurai bagaimana cara-cara budaya industri memproduksi dan mereproduksi suatu figur melalui teks dan praktik budaya secara beragam. Bennett dan Woollacott secara lebih jauh hendak mengeksplorasi mengapa dan bagaimana teks-teks tersebut mampu menciptakan daya tarik. Cara-cara yang berbeda dengan alasan-alasan yang berbeda. Memastikan popularitasnya akan terus berlangsung. [19] Sehingga tidak heran apabila kerap diciptakan semisal festival tahunan yang berkaitan dengan suatu mitos atau legenda tertentu di berbagai belahan dunia ini. Dalam konteks contoh disini adalah Festival Robin Hood.
Kaitan Khalayak dan Teks Populer
Lawrence Grossberg (1992) menyimpulkan secara apik mengenai kaitan khalayak dan teks popular. Ia menuliskan bahwa: Kita harus mengakui bahwa sebagian besar hubungan antara khalayak dan teks popular adalah hubungan yang aktif dan produktif. Makna teks tidak diberikan pada beberapa rangkaian kode yang tersedia secara terpisah dimana kita bisa mengonsultasikannya kapan saja kita sempat. Sebuah teks tidak menyandang politik atau maknanya sendiri yang telah ada di dalam dirinya sendiri; tak ada teks yang mampu menjamin efek apa yang akan terjadi. Orang-orang terus-menerus bersusah payah, bukan semata-mata menyimak dengan apa makna sebuah teks, tetapi untuk membuat sesuatu yang terkait dengan kehidupan, pengalaman, kebutuhan serta hasrat mereka sendiri menjadi bermakna. Teks yang sama bermakna berbeda bagi orang yang berbeda tergantung pada bagaimana teks itu diinterpretasikan. Dan orang yang berbeda punya sumber daya interpretatif yang berbeda sebagaimana mereka punya kebutuhan yang berbeda. Sebuah teks hanya dapat bermakna sesuatu dalam konteks pengalaman dan situasi khalayaknya. Yang tak kalah penting, teks tidak mendefinisikan bagaimana teks-teks itu digunakan atau fungsi-fungsi apa yang bisa dijalankan sebelumnya. Teks-teks dapat mempunyai kegunaan yang berbeda bagi orang yang berbeda dalam konteks yang berbeda… Bagaimana sebuah teks yang spesifik digunakan, bagaimana teks itu diinterpretasikan, bagaimana ia berfungsi bagi khalayaknya—semua ini terkait erat lewat pergumulan khalayak yang terus-menerus guna memahami dirinya sendiri dan dunianya, bahkan lebih dari itu, mewujudkan tempat yang lebih baik bagi dirinya sendiri di dunia. [20]
Akan tetapi media massa sebagai agen utama penyebaran budaya populer berupa teks populer tidak lepas dari kritik Noam Chomsky. Salah satu pemikir kenamaan ini mengatakan bahwa fakta berupa “teks populer” yang disajikan media massa dapat berarti hanyalah hasil rekonstruksi dan tidak sepenuhnya merupakan fakta yang sebenarnya. Karena itu harus disadari bahwa media massa merupakan alat ampuh dalam perebutan makna sekaligus memiliki kekuatan maha dahsyat dalam mempengaruhi masyarakat. [21]
Namun proses penyebaran berbagai teks tersebut tentunya kian dipermudah dengan adanya globalisasi yang menurut Anthony Giddens mempunyai berbagai dimensi pengaruh apalagi globalisasi telah menyebabkan dunia berada di luar kendali kita (runaway world) serta merombak cara hidup kita secara besar-besaran. [22]
Dalam industri budaya, tidak peduli apakah mitos dan legenda itu adalah “realitas” yang berasal dari yang nyata atau bahkan hanya fiksi dan fantasi dalam pijakan dasar teksnya. Yang paling utama adalah teks tersebut laku dijual dan mampu menjadi sumber kesenangan. Hal ini senada sebagaimana pernah diungkapkan Ien Ang bahwa fiksi dan fantasi adalah sumber kesenangan sebab ia menempatkan “realitas” dalam selingan karena ia membangun solusi imajiner bagi kontradiksi-kontradiksi nyata. [23]
Sementara itu, John Fiske (1987) berpendapat bahwa komoditas budaya yang memunculkan budaya massa setidaknya tersebar dalam dua ekonomi sekaligus yakni ekonomi financial dan ekonomi cultural. Ekonomi financial terutama menaruh perhatian pada nilai tukar, sedangkan ekonomi cultural terutama berfokus pada nilai guna—makna, kesenangan dan identitas sosial. Dimana interaksi antara dua ekonomi ini senantiasa berlangsung secara kontinu. Komoditas budaya yang berupa teks-teks tadi dapat dijual sekaligus menjadi sebentuk makna dan kesenangan bagi khalayak setelah terlebih dahulu tentunya melalui proses logika ekonomi. Fiske menegaskan bahwa semua itu terletak pada khalayak yang melakukan konsumsi. [24]
Membaca budaya popular berkaitan dengan konsumsi. Ideologi konsumerisme seakan menjadi pencarian yang tiada akhir dan tak mengenal habisnya. Setidaknya janji yang dibuatnya adalah bahwa konsumsi merupakan jawaban dari semua masalah kita, konsumsi akan membuat kita utuh kembali, konsumsi akan membuat kita penuh kembali, konsumsi akan membuat kita lengkap lagi, konsumsi akan mengembalikan kita pada kondisi “imajiner” yang diliputi kebahagiaan. [25]
Selanjutnya, apabila semakin kita menyelami buku ini maka aroma dan rasa dalam berbagai mitos dan legenda yang tersaji di dalam setidaknya akan memberikan gambaran betapa industri budaya telah merubah berbagai hal menjadi semacam komoditas budaya populer yang tentu saja berkaitan dalam rangka menceburkan diri dalam rimba ataupun lautan kapitalisme. Tabik.
Catatan
[1] Sebuah pengantar ringkas menyelami “Manusia-manusia Paling Misterius di Dunia”. Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 4, No. 2, Juli 2011. Disajikan ulang dengan beberapa penyesuaian.
[2] Nicholas Garnham, “On The Cultural Industries”, dalam Paul Marris and Soe Torham (Ed.), Media Studies: A Reader. Edinburg: Edinburg University Press, 1997.
[3] Lihat, John Storey. Pengantar Komprehensif Teori dan Metode Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop. Terj. Laily Rahmawati. Bandung: Jalasutra, 2007, hal. 32.
[4] Baca, Gerald Sussman. Communication, Technology, and Politics in The Information Age. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1997, hal. 34-35.
[5] Webster’s New World Encyclopedia. 1992. New York: Prentice Hall.
[6] Vincent Mosco. The Political Economy of Communication. Second Edition. London: Sage, 2009.
[7] Lihat, Burhan Bungin. Imaji Media Massa. Yogyakarta: Jendela, 2001, hal. 29; Stephen K. Sanderson. Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta: Rajawali, 1993, hal. 169.
[8] Lihat, Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992; Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington. The Future of The World Order: Masa Depan Peradaban dalam Cengkraman Demokrasi Liberal Versus Pluralisme, Cet. 2. Terj. Ahmad Faridl Ma’ruf. Yogyakarta: IRCiSoD, 2005, hal. 7-8.
[9] Lihat, Theodor Adorno and Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment. New York: Herder and Herder, 1972; Theodore Adorno. The Culture Industry. London: Routledge, 1991, hal. 86-87.
[10] Fred Inglis. Theory Media An Introduction. Massachusetts: Basil Blackwell Inc, 1990, hal. 114.
[11] Yasraf Amir Piliang. Hiperrealitas Kebudayaan. Yogyakarta: LKIS, 1999, hal. 32-33.
[12] Piliang, Op.Cit, hal. 33.
[13] Celia Lury. Budaya Konsumen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal. 62-63.
[14] Eka Nada Shofa Alkhajar, “Sinetron dalam Jeratan Industri Budaya”, Pelita, 29 April 2010.
[15] Dominic Strinati. Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer. Terj. Abdul Muchid. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, hal. 77.
[16] Storey, Op.Cit, hal. 157.
[17] Lihat, Henry Jenkins, Textual Poachers, New York: Routledge, 1992, hal. 53; Storey, hal. 162-163.
[18] Jenkins, Ibid, hal. 62.
[19] Tony Bennett and Janet Woollacott. Bond and Beyond. London: Mcmillan, 1987, hal. 20.
[20] Dikutip dari Storey, Op.Cit, hal. 8; Lihat pula, Lawrence Grossberg, “Is There a Fan in The House?: The Affective Sensibility of Fandom” In L. Lewis (ed.), The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media. London: Routledge, 1992, hal. 52-53.
[21] Denis McQuail. Mass Communication Theory. London: Sage Publication: 2002; Noam Chomsky. Kuasa Media, Terj. Nurhady Sirimorok. Yogyakarta: Pinus, 2005.
[22] Anthony Giddens. RUNAWAY WORLD: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita, Cet. 2, Terj. Andry Kristiawan S. dan Yustina Koen S. Jakarta: Gramedia, 2004, hal. xiv-xvi.
[23] Ien Ang. Watching Dallas. London: Methuen, 1985; B. Ashley (ed.) The Study of Popular Fiction. London: Pinter, 1989; Tony Bennett (ed.). Popular Fiction. London: Routledge, 1990; Tony Bennett, et.al (ed). Popular Culture and Social Relations. Milton Keynes: Open University Press, 1986.
[24] Lihat, Storey, Op.Cit, hal. 31-32.
[25] John Fiske. Reading Popular Culture. Boston, MA: Unwin Hyman, 1989.