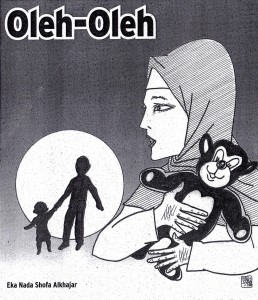Oleh-Oleh
Eka Nada Shofa Alkhajar
Dimuat di Solopos, 30 Mei 2014
Mentari pagi menyibak malam. Akhirnya hari yang kutunggu pun tiba. Seorang pemuda tampan lagi santun melamarku. Ini terjadi setelah sekian lama aku melangkahkan kaki, menelusuri dan melintas bumi. Akhirnya, kutemukan juga tambatan hatiku. Ia mampu mencairkan hatiku yang lama membeku di bawah terik matahari. Ia laksana lentera penerang dalam gelap dan sunyiku.
Tak lama berselang dari prosesi lamaran, akad nikah pun dilangsungkan. Sanak keluarga serta kolega berdatangan mengucap selamat atas pernikahan kami. Ini sekaligus menjadi ajang keluarga berkumpul setelah terpisah sekian lama. Pernikahan memang bukan sekadar menunaikan perintah agama. Lebih dari itu, ia adalah sarana manusia saling mengeratkan silaturahmi. “Alhamdulillah, semuanya lancar,” batinku.
Namaku Kirani. Aku terlahir di Kota Solo yang juga disebut Kota Bengawan. Namun, takdir membawaku bercengkerama dengan penatnya ibu kota negeri ini, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Panas, macet serta beragam polusi merupakan menu harian kota ini. Ya, aku bekerja di kota metropolitan, Jakarta. Aku bekerja di sebuah perusahaan bonafide yang bergerak dalam jasa riset pemasaran. Uang bukan masalah buatku. Gaji bulanan cukup besar, bahkan begitu besar untuk hidup di kota kelahiranku.
Di kota ini pula, salah satu rahasia takdir hidupku terungkap: jodoh!. Benar, kota ini yang mempertemukanku dengan seorang laki-laki yang kini menjadi suamiku, Mas Satrio. Kebetulan kami berada dalam satu perusahaan yang sama, hanya berbeda divisi kerja. Kami bertemu dalam sebuah rapat besar perencanaan tahunan perusahaan. Kami hanya curi pandang ketika itu. Hari berganti hari. Lambat laun, seiring waktu berjalan, kami pun dekat dan bersepakat menuju jenjang kehidupan baru: rumah tangga.
Masih segar dalam ingatanku, Mas Satrio pernah bertanya kepadaku, “Rani, maukah kamu menikah denganku dan menjadi istriku selamanya?” Aku pun menimpalinya dengan mengatakan, “Akan kujawab saat kamu menanyakan ini di depan orangtuaku!”. Hingga saat ini, aku kerap tersenyum sendiri manakala mengingat hal tersebut. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta. Sibuk bekerja dan mencari uang bukan hal baru bagi kami, hingga diriku mendapati kepastian hamil.
Aku mulai mengurangi porsi kerjaku dan sedini mungkin mengajukan cuti kerja. Semenjak masa kehamilan hingga kelahiran putri kami, Kinanti. Mas Satrio selalu penuh perhatian. Aku berucap syukur karena telah dikaruniai seorang anak perempuan cantik dan seorang suami yang baik. “Terima kasih yaa Rabbi,” ungkapku. Selesai memberi air susu ibu (ASI) eksklusif dan menimbang berbagai hal, kami pun sepakat menitipkan Kinanti pada kedua orangtuaku.
Sesungguhnya, kesepakatan ini tidak berjalan mulus. Mas Satrio menentang ide ini. Ia memintaku untuk fokus mengurus Kinanti. Sementara, ia bekerja untuk menafkahi keluarga. “Sudah, biar aku saja yang bekerja, kamu membesarkan Kinanti yaa,” ujar Mas Satrio kala itu.
Sebagai perempuan, aku pun merasa berhak untuk bekerja dan menghidupi diriku sendiri sekaligus mampu menambah penghasilan keluarga. Semuanya adalah untuk kebaikan keluarga, demikian pikirku. Aku tak segan berdebat dengan suamiku demi mempertahankan keyakinan tersebut. “Walau bekerja, aku kan tetap bisa menengok Kinanti, toh setiap bulan aku akan pulang,” kataku mengakhiri sebuah perdebatan.
Waktu terus berjalan, bulan berganti bulan. Akhirnya Mas Satrio memilih untuk menyusul Kinanti. “Ma, kalau begitu biar aku yang menjaganya. Aku akan mencari pekerjaan lagi di sana,” kata dia kepadaku. Aku terus melangkah dan meneruskan karier. Semakin lama karierku semakin menanjak, demikian juga dengan materi yang kudapatkan. Mulanya, setiap bulan aku bisa menepati janjiku untuk pulang.
Tak lupa, oleh-oleh pesanan Kinanti selalu hadir bersamaku. Boneka, tas, gelang dan kalung adalah favoritnya. Selalu ada senyuman dari bibir mungilnya saat menatapku tiba. Tawa riangnya pun menggema ketika kuberikan oleh-oleh yang kujinjing. Namun, beban kerja yang kian padat dan menumpuk membuatku ingkar dan menjadikannya alasan menunda pulang. Kadang dua sampai tiga bulan sekali aku baru pulang.
Akan tetapi, bingkisan oleh-oleh selalu kukirimkan melalui jasa kurir untuk memastikan Kinanti selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Kinanti kini sudah dapat berkata-kata. Sapaan “Mama” membuatku makin bahagia. “Mama, hati-hati ya. Semoga lancar perjalanannya. Cepat pulang lagi, Ma,” ungkapnya fasih tatkala mengantarku memasuki pintu bandara Adi Soemarmo.
Aku selalu berpikir, berbagai oleh-oleh sudah cukup untuk sekadar memberikan kegembiraan bagi anakku. Namun, ternyata semua itu salah. Kinanti memang senang sekali karena selalu mendapat oleh-oleh manakala kupulang. Akan tetapi, sejatinya, ia lebih bahagia karena bertemu denganku. Bersama denganku walau hanya beberapa saat. Pada bulan ke-12 kepulanganku. Di pintu kedatangan bandara, senyum dan oleh-oleh di tangan yang kubawa tak berbalas senyum di wajah Kinanti.
Hanya suamiku yang selalu tersenyum menyambutku. Melihat perangai Kinanti yang tak biasa menghadirkan firasat padaku. Dan benar saja, dalam jarak selangkah, Kinanti yang semenjak tadi diam membatu akhirnya angkat bicara. Lirih tapi pasti. “Mama, Kinanti sudah nggak mau oleh-oleh lagi”. Aku pun terhenyak. Aku menatap mata Kinanti dalam-dalam. Aku tahu, ia masih ingin meneruskan kata-katanya. “Sudah cukup puluhan oleh-oleh itu. Kinanti tidak mau lagi!”.
Hatiku berdegub keras mendengarnya. Aku mulai mencerna dan menerka keinginan Kinanti. Belum sampai kutemukan jawaban, Kinanti melanjutkan lagi, “Kalau boleh Kinanti mau meminta oleh-oleh terakhir saja!”. Spontan kujawab, “Boleh, apa itu, Nak? Pasti Mama berikan”. “Mama jadilah oleh-oleh terakhir Kinanti. Jangan kembali lagi ke Jakarta. Tinggallah bersama Kinanti, Ma,” kata dia.
Mendengar ungkapan hati dan permintaannya yang tulus. Air mataku pun meleleh. Sesaat kemudian tumpah tak terbendung. Suamiku pun tampak membisu tak percaya Kinanti dapat berkata demikian. Kami menghambur bersama dalam pelukan. Aku baru menyadari, selama ini, aku memiliki keluarga yang lebih berharga dari apa pun. Suamiku dan Kinanti telah menggenangkan cinta.
Sekian lama, mereka memilih mengalah untukku. Suamiku berhenti dari pekerjaannya menyusul Kinanti. Sementara Kinanti, ia telah bersabar tanpa kasih sayang seorang ibu karena sejak kecil tinggal bersama kakek-neneknya. Aku seperti tak pernah sadar sepenuhnya kalau aku memiliki keluarga yang luar biasa. Suami dan anakku layak mendapatkan kasih sayang penuh dariku.
Sejak saat itu, aku memutuskan untuk menjadi oleh-oleh terakhir Kinanti dan oleh-oleh terindah untuk suamiku. Dan kami mulai menapaki hari baru hidup bersama sebagai keluarga. Semua ini mengajarkanku sebuah pelajaran penting: kasih sayang adalah pengikat hati dan penguat cinta. “Alhamdulillah. Yaa Rabbi mudahkanlah jalan kami”, begitu kalimat doaku.